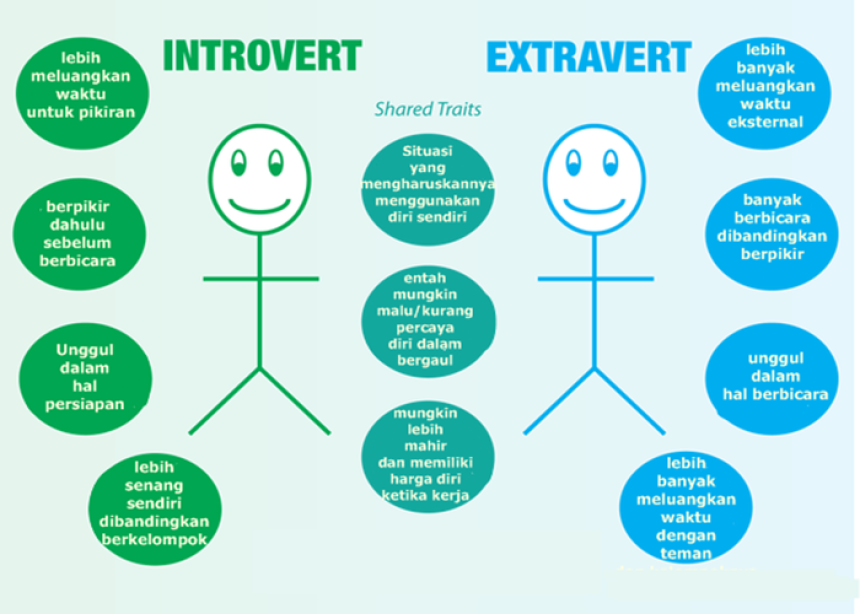Pengungsi di Bawah Beringin
Kisah ini adalah fiksi semata. Harap pembaca bijak menyikapi isi cerita dan mencari sumber sejarah yang terpercaya untuk mengetahui peristiwa sebenarnya.
Pagi di Yogyakarta, 19 Desember 1948 adalah fajar yang berlumuran darah. Kokok ayam dan aroma kopi digantikan oleh raungan pesawat pemburu yang mencakar langit sunyi sebuah melodi kehancuran. Agresi Militer Belanda II telah dilancarkan. Kota itu, jantung Republik yang berdetak kencang, mendadak menjadi sarang badai yang mematikan. Perjanjian Renville yang seharusnya menjadi jangkar perdamaian, kini hanyalah selembar kertas usang yang diinjak-injak. Di sebuah rumah kecil beratapkan genteng tua di pinggiran kota. Danu seorang pemuda delapan belas tahun gemetar. Ia adalah penjual koran, tetapi di balik tumpukan berita ia adalah anggota pemuda Republik. Ia memiliki adik perempuan bernama Sari, yang kakinya lumpuh karena penyakit Polio. Sari adalah cahaya lilin yang tidak pernah padam bagi jiwa Danu yang selalu tegang.
Pagi itu, radio usang mereka merintih pilu menyiarkan kabar pahit.
“Lapangan Udara Maguwo telah jatuh dan pemimpin Republik ditangkap.” Danu memeluk Sari.
Air mata menggenang di pelupuknya seperti embun pagi yang keruh. “Kita harus pergi Sari, sekarang juga,” bisiknya. Suaranya adalah bisikan keputusasaan yang mengandung tekad.
Saat Danu menyiapkan gerobak kayu kecilnya, Sari menunjuk ke sebuah kotak kayu jati tua yang disembunyikan di balik lemari. “Kotak ayah, Kak. Ayah bilang kalau ada ‘suara baja di udara’ kita harus membukanya.”
Ayah mereka yang meninggal setahun lalu saat gerilya di Jawa Timur adalah seorang juru kunci keamanan kota yang misterius. Danu tidak pernah mengerti, ia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan harta, melainkan peta kota yang sangat detail, beberapa lembar sandi, dan sebuah kunci kuning kecil dengan ukiran elang. Peta itu menunjukkan jalur evakuasi rahasia, sebuah urat nadi tersembunyi di bawah kota yang seharusnya hanya diketahui oleh petinggi militer. Danu memutuskan, ia harus menggunakan jalur itu. Kunci itu terasa dingin seperti baja di tangannya.
Danu memasukkan Sari ke gerobak yang biasa digunakannya untuk mengangkut koran, kini menjadi perahu kecil di tengah banjir pengungsi. Mereka harus menuju selatan, ke Desa Pleret tempat bibi mereka tinggal. Arus pengungsi mengalir seperti sungai yang ketakutan, membawa serta kepanikan dan harta benda seadanya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok kecil tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) yang berdiri di depan jalan, senapan mereka mengarah tajam seperti jari menunjuk pada nasib buruk.
Seorang tentara senior dengan kumis tebal maju. “Mau kemana Kalian? Semua warga harus kembali ke rumah masing-masing! Kota aman di bawah perlindungan Ratu.” Suaranya mengguntur, memerintah tanpa kehangatan.
Ketakutan mengepung Danu seperti jaring laba-laba. Sari menarik lengan baju kakaknya. Sari butuh obat yang hanya bisa didapat di Pleret. Danu mengeluarkan peta warisan ayahnya, menunjukkan rute alternatif yang ia yakini aman.
Tapi saat itu ia memasukkan kembali peta itu ke saku, tentara KNIL itu melihat sekilas lembaran kertas usang tersebut. “Hei, kamu! Pemuda gerobak, apa itu yang kamu sembunyikan?!” tanya tentara itu, matanya tajam seperti mata elang.
Danu panik.”Ini…….ini hanya peta untuk mencari alamat dokter di kota, Tuan. Adik saya sakit.” Danu berusaha terlihat selugu mungkin.
Tentara itu mendengus curiga. “Peta terlalu rapi untuk mencari dokter biasa dan kamu itu pemuda bukan?” ia menendang pelan gerobak Danu. Tapi Danu terus berusaha menyembunyikan kertas itu.
“Balik! Atau kau akan tahu akibatnya.” Danu tahu ia harus bertindak. Berbalik berarti terjebak maju berarti tertembak.
Danu melihat parit kecil di tepi sawah yang berlumpur, itu adalah sebuah kesempatan. “Tuan” kata Danu, suaranya berusaha dibuat tenang, “Kami hanya ingin kembali ke kota, adik saya sakit.” Saat tentara itu lengah memeriksa barang bawaan pengungsi lain, Danu melihat celah. Ia segera mendorong gerobaknya dengan sekuat tenaga ke arah parit. “Sari pegangan yang kuat!” seru Danu.
Gerobak itu terjerembab dan terguling di parit berlumpur. Tindakan itu memicu kepanikan di barisan pengungsi. Tentara itu marah, “Berhenti!” teriak mereka. Danu kini berlumur lumpur, bangkit. Ia menarik gerobaknya yang terjebak. Lumpur menghimpitnya seperti cengkraman raksasa, tetapi tekadnya sekeras baja yang ditempa. Ia berteriak kepada pengungsi lain, “Lari, jangan biarkan mereka menahan kalian.” Tentara mulai menembakkan tembakan peringatan ke udara.
Suara tembakan itu memekakkan telinga dan membuat burung-burung terbang histeris meninggalkan sarangnya. Namun, Danu berhasil menyeret gerobaknya menjauhi kerumunan, masuk ke dalam semak belukar yang lebat, bersembunyi seperti kijang yang terluka.
Di tengah semak, napas mereka tersengal seperti kehabisan udara. Mereka selamat dari tembakan, tetapi kini benar-benar terisolasi. Saat Danu mencoba membersihkan lumpur di sekitar gerobak, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di bawah akar beringin kecil. Itu adalah pintu besi yang tersembunyi, mengingat kunci elang milik ayahnya, ia memasukkan kunci itu. “Klik” pintu besi itu terbuka, menampilkan sebuah tangga batu yang menurun dalam kegelapan. Pintu rahasia yang tertera di peta ayahnya adalah sebuah kenyataan.
“Ini jalan Ayah,” bisik Sari, matanya berkilauan penuh takjub. Danu tahu ini adalah risiko besar, tetapi kembali ke jalan utama adalah risiko yang lebih besar. Ia menggendong Sari dan turun.
Di dalam terowongan itu, udara dingin dan lembap, berbau lumut dan tanah tua. Terowongan itu sempit dan gelap. Danu menggunakan korek api seadanya sebagai penerangan. Jalur itu ternyata adalah saluran irigasi kuno, kini tidak terpakai, yang menjalar di bawah sawah dan desa. Mereka berjalan merangkak dan sesekali membungkuk.
Sari, meskipun ketakutan justru menemukan kekuatan. “Kak, di luar sana mungkin mereka sudah mengira kita hilang, mengira Indonesia sudah habis. Tapi di sini, di bawah tanah ini, kita masih bernapas untuk Republik, kan?”
Danu memeluk adiknya. Ia mengeluarkan singkong rebus dari saku.”Tidak, Sari. Indonesia tidak akan hilang. Lihat,” katanya, menunjuk ke arah daun-daun yang baru tumbuh dari celah batu, “bahkan setelah badai, ada harapan baru.” Saat mereka beristirahat, Danu melihat ada coretan samar di dinding terowongan.
Bukan coretan biasa, melainkan simbol-simbol yang sama persis dengan yang ada di peta ayahnya. Ayahnya adalah juru kunci dari jalur pelarian bawah tanah ini.
Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan berjam-jam, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang terkunci di bawah tanah, tempat jalur itu terbagi dua. Danu menggunakan kunci elang itu lagi. Di dalam ruangan itu, ada bangku kayu dan sebuah peti kecil. Di atas peti, ada surat yang tertutup debu, ditujukan kepada ‘Danu dan Sari’. Itu adalah tulisan tangan ayah mereka.
“Anak-anakku, jika kalian membaca ini berarti suara baja telah datang. Kunci elang ini adalah amanah. Jalur ini bukan hanya untuk pelarian, ia adalah jalur logistik terakhir. Di peti ini, ada peta sandi yang lebih lengkap dan di sana di balik dinding batu ini, tersembunyi radio pemancar kecil. Jangan lari ke Pleret. Radio ini adalah tugasmu, kirim pesan terakhir ini 'Elang telah hinggap di Sarang Rajawali. Bawa semua ke Timur'. Itu adalah sandi untuk mengalihkan logistik yang tersisa ke markas lain. Tugasmu bukan hanya mencari obat, tetapi menjadi suara harapan yang terputus."
Danu membaca surat itu, ia terkejut. Firasat buruknya kini menjadi kenyataan yang pahit. Ayahnya meninggal bukan karena gerilya biasa, ia adalah intelijen utama dan Sari membutuhkan obat, tetapi tugas negara memanggilnya lebih dulu.
Danu melihat Sari yang kini menatapnya dengan mata sepenuh tekad. “Kita tidak akan pergi ke Pleret dulu, Kak. Obat bisa menunggu. Tapi pesan ini tidak.”
Danu mengangguk, ia membuka peti. Di dalamnya ada radio pemancar kecil, berdebu, tetapi masih berfungsi. Danu, berbekal pengetahuan sandi rahasia yang ia pelajari dari ayahnya bertahun-tahun lalu, sebuah ilmu yang kini berharga melebihi emas. Danu segera mengambil posisi.
Jari-jari gemetarnya mulai menekan tombol pemancar. Bunyi ‘tittat’ dari frekuensi radio itu terdengar pelan namun pasti, mengalir seperti bisikan sunyi yang menembus kegelapan dan keheningan di bawah tanah. Pesan itu terkirim, isinya adalah kode mendesak “Elang telah hinggap di Sarang Rajawali. Bawa semua ke Timur”. Itu adalah sandi yang sangat penting yang berarti seluruh persediaan logistik utama perjuangan harus segera dialihkan ke markas aman. Danu tahu kode yang baru saja ia kirimkan telah menjadi garis hidup yang menyelamatkan ratusan nyawa yang kini terancam di pusat kota.
Setelah memastikan pesan itu terkirim, Danu dan Sari mematikan radionya. Mereka meninggalkan peti dan petanya di ruangan itu, mengunci pintu besi. Mereka harus melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya keluar dari terowongan.
Di sebuah sumur tua di pinggir desa. Mereka berhasil mencapai Pleret. Bibinya, seorang wanita paruh baya dengan hati seluas samudra, menyambut mereka dengan air mata dan segera memberikan obat untuk Sari.
Mereka selamat tetapi Danu kini membawa beban baru. Ia bukan lagi hanya penjual koran atau anggota Pemuda Republik. Ia kini adalah juru kunci rahasia yang baru.
Sebuah gubuk sederhana tempat Danu dan Sari berlindung, ia memeluk adiknya seraya menatap ke arah langit yang kini kembali biru dan tenang, sebuah kebohongan yang menyakitkan.
“Kita sudah mengirim pesan Ayah, Sari. Sekarang kita harus melanjutkan perjuangan di desa. Kita harus menjadi api kemerdekaan yang menyebar,” kata Danu.
Sari tersenyum. “Kita adalah juru kunci, Kak. Kita akan menjaga rahasia ini sampai fajar kebebasan yang sejati datang.”
Danu berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap langkahnya, setiap napasnya, akan menjadi bagian dari usaha untuk mengakhiri agresi, bukan hanya karena tugas negara, tetapi karena ia tahu rahasia di bawah tanah yang ia jaga kini menjadi kunci nasib bangsa yang masih berjuang di permukaan.
“Agresi Militer Belanda 2 adalah kegagalan perjanjian Renville dan keinginan untuk menguasai kembali seluruh wilayah indonesia secara paksa. Karena Belanda merasa Indonesia tidak patuh pada perjanjian tersebut dan ingin melumpuhkan pemerintahan Indonesia dengan menyerang Ibu Kota Yogyakarta.”