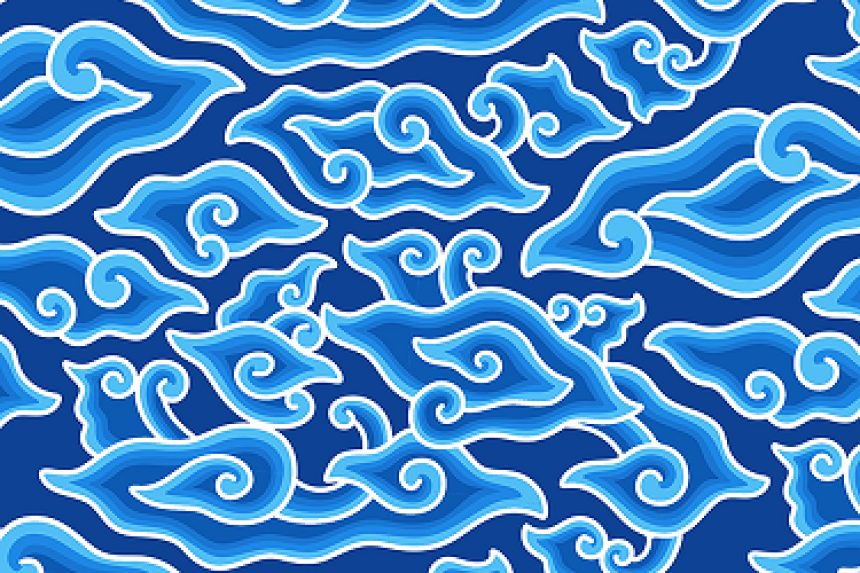Perihal Bapak
“Pada akhirnya, apa-apa di dunia ini yang kau percayai sebagai sebuah niscaya, semua berakar pada satu hal; perbedaan. Maka, jika kau benar memahami dua hal tersebut, sudah sepatutnya kau mengerti apa yang terjadi setelahnya; perselisihan. Hanya jangan lupa, kalau itu semua terjadi di luar batas kemampuan setiap insan. Jadi, tak seharusnya kau menyalahkan makhluk tunggal bernyawa yang kau sebut sebagai; manusia.”
1948, Jakarta.
Jauh sebelum aku berpikir tentang satu dua kemungkinan yang kenyataannya, benar-benar terjadi, Bapak lebih dulu memberiku pesan. Bahwa kelak, sekecil apa pun amarah yang tersimpan dalam benak, jangan pernah perlihatkan pada apa-apa yang bernyawa. Utamanya manusia. Karena, mustahil hukumnya jika pertentangan menjadi hal yang terhindarkan. Sayangnya, aku terlambat menyadari maksud di balik perkataan Bapak kala itu. Beberapa tahun berselang, barulah aku benar-benar mengerti mengapa hal itu menjadi perkataan yang selalu Bapak tekankan. Karena ternyata, bentuk kesadaran yang aku terima bukan lagi dalam bentuk sebab, melainkan konsekuensi.
Cerita ini terjadi ketika Indonesia masih seumur jagung. Bermula ketika Bapak memanggilku untuk ikut dalam sebuah pertemuan. Waktu itu, aku memasuki usia kedelapan, yang artinya sama dengan tahun ketiga di sekolah dasar. Aku menyanggupi permintaan Bapak saat itu, karena aku juga penasaran dengan organisasi yang Bapak pimpin. Jika ditanya perihal pekerjaan, Bapak tak pernah memberi jawaban pasti dari setiap pertanyaan yang terlontar. Jangankan aku anak semata wayangnya, Ibu yang sudah menemani Bapak sejak 13 tahun yang lalu saja selalu mengedikkan bahu setiap kali aku bertanya mengenai kepastian pekerjaan Bapak. Maka dari itu, ajakan Bapak saat itu aku anggap sebagai kesempatan emas untuk menelusuri sisi lain Bapak. Pagi itu, aku bersemangat menghabiskan sarapan di meja makan, tidak sabar untuk pergi bersama Bapak.
“Bapak dengar, ada murid baru di sekolahmu, Dera?” Bapak berucap seraya menghabiskan sepiring nasi goreng pedas buatan Ibu. Kadang diselingi dengan menyesap secangkir kopi hitam pekat yang tak pernah absen dari meja makan.
“Iya, Pak. Namanya Artha. Ternyata, ia lahir di tanggal dan bulan yang sama denganku. Hanya saja, ia lahir setahun lebih dulu. Selain itu, tak banyak hal yang Dera tahu tentang Artha, anaknya cenderung tertutup dan suka menyendiri, Pak.”
“Hm, orang mana dia? Dilihat lihat namanya seperti nama kalangan pribumi?”
“Sudah Dera bilang, tidak tahu, Pak. Buat apa juga cari tahu, anaknya terlalu pendiam, gak asyik. Mana bisa Dera berteman sama si Artha-Artha itu.”
“Ya sudah, kalau Dera tidak tahu. Bapak cuma penasaran saja, si Artha-Artha itu orangnya seperti apa. Cepat habiskan sarapanmu, Dera. Katanya mau ikut Bapak pergi?”
“Siap 86, Pak!”
***
“Mana bisa begitu, Muso? Konyol sekali caramu, kalau begitu, anak 5 tahun juga enggan menuruti perintahmu. Ayolah, kita ini PKI. Radikal, Brutal. Kata ‘lembut’ sama sekali tidak pernah ada dalam kamus kita!”
“Tenang, Saudara Amir. Saudara Muso hanya menyampaikan pendapat, tidak perlu saudara tanggapi dengan emosi.”
“Tapi apa yang Saudara Muso sampaikan sama sekali bukan ciri khas PKI dalam menyerang. Kalau sudah tidak bisa bersikap radikal, keluar saja dari organisasi ini! Atau jangan-jangan, sebenarnya saudara Muso adalah seorang penyusup suruhan Bung Karno?”
“MAKSUDMU APA, SAUDARA AMIR!? Saya sama sekali tidak tertarik mengikuti pemikiran, ajaran atau bahkan menjadi orang suruhan Bung Karno! Saya tidak sudi, dan tidak akan pernah sudi. Camkan itu, Amir Sjarifuddin!”
“Rupanya Saudara Muso ini pandai membela diri. Jika saudara sungguhan berada dipihak kita, seharusnya saudara tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan target!”
DEG! Ketika mendengar beberapa nama yang disebut, pikiranku mendadak ribut. Nama itu, Ya Tuhan. Umurku memang bisa dibilang terlalu belia untuk memahami hal-hal kompleks seperti politik, ideologi, radikal atau bahkan menjelaskan apa itu PKI. Tetapi aku berani bersumpah bahwa selama ini, Bapak telah terjerumus dalam organisasi terlarang. Tadinya, dengan semangat dan rasa antusias yang tinggi, aku semangat melangkahkan kaki bersama Bapak menuju suatu gedung pertemuan yang berlokasi tidak jauh dari rumah. Sayangnya, perasaan antusias dan semangat itu tak berlangsung lama, sebab dengan lekas rasa keterkejutan sekaligus ketakutan memenuhi kepala. Bersamaan dengan gerakan Bapak yang dengan pelan membuka kusen pintu, netraku menangkap suatu poster dengan warna mencolok yang terpajang rapi di sudut ruangan. Sebuah poster propaganda yang beberapa hari lalu sempat menggemparkan warga kampung. Tidak salah lagi, gedung ini adalah tempat persembunyian utama organisasi Bapak, Partai Komunis Indonesia.
Kupikir, Bapak tidak ada kaitannya dengan organisasi terlarang itu. Di mataku, Bapak memiliki wibawa dan jiwa pemimpin yang memancar kuat tiap kali beliau berbicara. Tapi tidak untuk hal ini. Mengetahui fakta bahwa ternyata, aku, Kamadera Aradhi, adalah anak pimpinan Partai Komunis Indonesia, seketika mengubah persepsiku terhadap Bapak. Apa kata teman-temanku di sekolah kalau ternyata selama ini, Bapak menjadi bagian dari organisasi terlarang yang merenggut nyawa beberapa orang tua mereka? Bahkan, Bapak menjadi pemimpin tertingginya?
Aku masih sibuk menetralkan detak jantung yang bergemuruh saat rapat masih berlangsung. Perdebatan yang terjadi antara 2 anggota–yang konon aku tahu sebagai Muso dan Amir Sjarifudin itu belum menemui titik temu. Mereka masih terus saling menyalahkan, memojokkan satu sama lain. Bapak selaku pemimpin rapat pagi itu pun tidak dapat berbuat banyak selain berusaha menengahi. Bukan Bapak namanya jika tak terbiasa menghadapi situasi apa pun dengan kepala dingin. Orang kalau sudah terbawa suasana, logikanya dinomor duakan, Dera. Bahkan bisa tidak berfungsi–cuma mengandalkan emosi saja. Nanti, suatu hari Dera akan paham, kenapa Bapak selalu bilang pentingnya menjaga emosi. Semarah apa pun Dera nantinya, ingat pesan Bapak, ya? Tak berselang lama, suara tamparan tiba-tiba terdengar menggema di langit-langit ruangan. Muso baru saja menampar Bapak. Aku yang masih tenggelam dalam pikiranku sendiri lantas terperanjat bergegas menghampiri Bapak. Tak peduli dengan larangan Bapak yang memintaku untuk tetap diam selama rapat.
“BAPAK!!!!!” Aku berteriak histeris saat mengetahui kondisi Bapak yang tersungkur mengenaskan–ada darah mengalir di sudut bibirnya. Sekeras itukah tamparannya?
“Ya Tuhan, Aidit ternyata membawa anaknya. Bisa runyam urusannya kalau begini.”
“Ternyata selama ini Aidit punya anak? Kukira ia memilih untuk melajang.”
“Bah, apa pula tujuan Aidit membawa anak kecil dan kurus macam dia? Menambah beban saja.”
Awalnya, aku tak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Aku hanya fokus membantu Bapak berdiri–membersihkan sudut bibirnya yang berdarah. Memastikan kondisi Bapak seraya membujuknya untuk membalas perlakuan anggotanya barusan. Menurutku, itu keterlaluan. Kekanak-kanakan. Jika aku ada di posisi Bapak, kuusir saja 2 orang pembuat masalah itu. Kalau perlu, kuancam mereka dikeluarkan dari partai jika masih terus menyalahkan satu sama lain. Benar-benar membuang waktu. Sesuai dugaan, adalah sebuah kemustahilan seorang Bapak bertindak demikian. Sudah kubilang, Bapak selalu bisa mengesampingkan emosinya–bahkan di saat seperti ini. Bapak lebih memilih untuk tetap bersikap tenang seperti sebelumnya, bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Beliau memintaku untuk bergegas kembali ke tempat semula–duduk rapi di sudut ruangan. Gedung ini hanya terdiri atas dua ruangan. Sepetak dapur disertai dengan toilet kecil, dan ruang serbaguna yang saat ini tengah menjadi saksi keributan. Namun, tiba-tiba indera pendengaranku menangkap salah satu ucapan yang seketika menyulut emosiku–ini keterlaluan. Muso, sang biang keributan, dengan santainya berucap:
“Rupanya kita punya kejutan lain di sini. Lihat, anak kecil berlagak sok pahlawan yang terduduk di sudut ruangan itu ternyata anak Aidit. Tidak tahu saja dia, hanya seorang anak hasil perselingkuhan yang mengira Bapaknya benar-benar menyayanginya. Populasi orang-orang menyedihkan semakin bertambah saja.”
Segera setelah mencerna satu dua kalimat Muso, secepat itu pula aku beranjak dari kursi. Tidak peduli dengan puluhan pasang mata yang lekas menjadikanku objek pandang ketika aku sengaja menghempaskan kursi yang aku duduki secara kasar. Aku belum mengerti istilah dewasa seperti selingkuh waktu itu. Tapi aku tidak bisa menahan diri ketika Muso mengatakan bahwa Bapak tidak benar-benar menyayangiku. Tidak, Bapak sungguh-sungguh menyayangiku, sungguh-sungguh menganggapku anaknya, darah dagingnya. Seburuk-buruknya Bapak, meskipun aku tidak pernah benar-benar tahu watak perilaku Bapak, aku yakin Bapak akan tetap menyayangiku, menyayangi putri kecilnya–Dera-nya. Dan selamanya akan tetap begitu.
Aku berjalan cepat menghampiri sumber suara–Muso. Baru benar-benar menyadari kalau ternyata dia memang menjadi antagonis di sini–walaupun semua yang ada di ruangan ini antagonis–faktanya memang begitu. Dengan sisa-sisa keberanian yang tersisa, aku memberanikan diri untuk menggebrak meja tepat di hadapan Muso. Untuk ukuran anak 8 tahun, postur tubuhku bisa dibilang cukup tinggi. Sehingga mudah saja untuk aku melakukannya. Muso tidak bergeming–tetap diam di tempatnya. Hanya pelototan matanya yang aku terima. Tidak puas dengan reaksinya, aku mencoba melakukan sesuatu yang lebih gila. Mengabaikan dua hal penting–ucapan Bapak beberapa saat yang lalu, serta aku dan Muso yang entah sejak kapan sudah menjadi pusat perhatian. Di sekolah, aku punya guru bela diri. Walau baru beberapa minggu aku ikuti, tetapi aku merasa itu sudah cukup untuk setidaknya memberi Muso sedikit pelajaran untuk tidak berkata sembarangan. Aku mulai mengambil ancang-ancang–dengan brutal melompat ke atas meja. Terdengar suara tertahan–tetapi sekali lagi, aku tidak peduli. Muso ikut berdiri dengan raut terkejutnya. Bertanya-tanya apa yang hendak aku lakukan. Kulemparkan senyum tipis mengejek seraya berkata,
“Je houdt echt van me, Muso. Onthou dat goed.”
Aku tidak tahu apakah Muso mengerti maksud kalimatku barusan. Setelah berucap demikian, sebelah kakiku berhasil mendarat pada pipinya. Ya, aku barusan menendangnya–mempraktikkan salah satu jurus yang aku pelajari di sekolah. Tidak sempat mengantisipasi, Muso kontan terpelanting ke belakang. Menilik posisi Muso yang lengah, aku kembali melompat dari atas meja dan tepat mendarat di atas perutnya. Pukulan-pukulan kembali kulayangkan tepat di atas wajahnya, seolah olah wajahnya adalah arena samsak tinju yang empuk. Aku benar-benar lupa ucapan Bapak beberapa saat lalu–lagi pula anak kecil mana yang terima mendengar perkataan menyakitkan itu?
Kembali di ruang rapat, aku masih sibuk melayangkan pukulan dan tendangan. Orang-orang yang tadinya berusaha menarikku mundur, berhasil kusingkirkan satu persatu. Hah, apa-apaan orang-orang ini, badan besar omongan kasar, nyatanya melawanku saja tidak mampu. Tak lama, Bapak dengan tergesa-gesa menghampiriku. Rupanya beliau baru saja kembali dari toilet dan tak tahu menahu mengenai apa yang bisa membuatku bertindak sedemikian brutalnya. Bapak berteriak memanggil namaku, menyuruhku berhenti. Sekali, dua kali, tiga kali, namun aku abai. Ketika Bapak tepat berada di depanku, dengan Muso yang berkali-kali mengerang kesakitan, tanpa babibu langsung menarikku menyingkir dari atas Muso. Tanganku yang masih sibuk memukuli Muso tak sengaja mengenai pelipis Bapak, membuat warna merah tercetak jelas. Tidak, aku tak pernah mengira pukulanku–yang tidak sengaja itu–bisa mendarat pada pelipis orang yang paling aku sayangi. Aku kontan memeluk Bapak–berkali kali merapalkan maaf atas pukulanku yang tak sengaja melukainya. Bapak balas memelukku, mencium puncak kepalaku yang sudah tak karuan. Pelukanku dan Bapak tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Muso bangkit dari posisinya, dengan mengacungkan senapan, yang dengan cepat mengurai pelukanku dan Bapak.
Dengan gerakan cepat, Bapak lantas menarikku ke belakang–menyembunyikanku tepat di belakang tubuh besarnya. Tubuhku mendadak gemetar melihat moncong senapan yang sekarang tepat mengarah ke kepala Bapak.
“Semua ini ulah anak sok pahlawanmu itu, Aidit. Rapat hari ini berjalan kacau, buntu tanpa hasil. Yang ada hanya sesi pertikaian tidak jelas ditambah aksi anak kecilmu itu.”
“SEMUA INI BERAWAL DARIMU, MUSO!!!” Ya, aku mengatakan itu tepat di depan wajahnya. Aku berontak dari cekalan tangan Bapak, Tidak peduli dengan intonasi suaraku yang meninggi serta aku memanggilnya tanpa sebutan ‘Pak’ atau ‘Tuan’. Kini senapan itu beralih mengarah padaku–Muso tepat menodongkannya pada dahiku.
“Sudah aku bilang, anak ini memang sok pahlawan. Katakan, kau mau apa, anak kecil? Kau ingin aku membunuh Bapakmu atau dirimu sendiri?”
“KETERLALUAN!!”
Singkat cerita, setelah melalui adu mulut yang nyaris tak berujung itu, aku memberanikan diri untuk merampas senapan itu dari genggaman Muso. Ketika Muso masih menyelesaikan serentetan kalimat panjangnya, secara tiba-tiba aku menggenggam moncong senapan, hendak merebutnya. Namun terlambat, Muso lebih dulu menyadari pergerakanku. Saat tanganku menggeser posisi moncong, saat itu juga Muso menarik pelatuk senapan, menimbulkan suara bising senapan tepat ditelingaku.
DOR! DOR!
Sepersekian detik, otakku baru memproses apa yang terjadi. Segera setelah tembakan itu, aku mendengar suara orang terjatuh tepat di belakangku. Kepalaku menoleh bersamaan dengan ambruknya tubuh Bapak–Muso baru saja melepaskan peluru dan tepat mengenai Bapak. Tubuhku seketika mematung, menyadari bahwa secara tidak langsung, aku menjadi penyebab Bapak meregang nyawa.
Dengan pelipis yang berlumuran darah, aku terduduk kaku memeluk tubuh Bapak yang tergeletak. Seketika tangis histerisku bergema memenuhi ruangan yang tadinya lengang–hanya diisi oleh suara kegaduhan Muso. Apa yang baru saja aku lakukan?