
The Sanctuary
Harapan, keberanian, dan tekad dalam ketidakpastian. Sebuah kisah pada peristiwa The Blitz.
And in the end, all I learned was how to be strong.
Alone.
***
Oxford, Inggris, September 1940.
Iris masih berumur 21 tahun ketika ia sedang merapikan barang-barang yang berserakan dan menutup pintu laboratorium. Sebelum menghubungi teman-temannya, ia mengumpulkan berkas-berkas hasil kerjaannya hari ini kepada sang dosen.
“Cepat, Iris!” Seruan Martha, teman satu jurusannya terdengar sesaat setelah telepon umum terangkat. Sore ini, Iris, bersama beberapa temannya akan merayakan salah satu dari mereka yang telah terpilih menjadi perawat tetap di Rumah Sakit Royal London.
“Tunggu sebentar! Rayakan saja dulu tanpa aku.” Iris merapatkan jaketnya. “Sudah, ya. Aku tutup teleponnya!”
Setelah buru-buru menutup pintu bilik telepon umum, gadis itu mempercepat langkahnya menuju The Turf Tavern Oxford, tempat titik temu teman-temannya, yang berjarak sekitar sembilan menit dengan berjalan kaki.
Pemandangan restoran kecil yang asri dengan banyaknya bunga di sekeliling bangunannya memanjakan mata Iris setelah seharian menatap berbagai macam lembar praktek. Ia membuka pintu masuk dan langsung bergabung dengan empat temannya, mereka sudah memesan begitu banyak makanan.
“Wah! Satu personel sudah bergabung, teman-teman!” Flint berdiri dan menyambut Iris dengan tos tangan khasnya, bersambung dengan Geoff.
“Keren sekali kalian, pesan begitu banyak makanan sampai begini!” Iris takjub melihat meja mereka.
“Pasti! Ini semua demi Ms. Hart kesayangan kita!” Martha merangkul pundak Valentina, senyuman gadis itu melebar.
Iris duduk di samping Geoff dan Martha, mereka berlima mulai memanjatkan doa untuk kelancaran pekerjaan baru Valentina, dan keselamatan keluarga mereka yang tengah bergabung dalam medan perang. Setelahnya, mereka menyantap hidangan di depan mata: roti, teh hangat, sup, dan pai daging mini–setidaknya hanya menu-menu itu yang tersedia beberapa bulan ini di penjuru Inggris–sambil bercerita tentang kehidupan mereka setelah hampir sebulan tak berkumpul.
Di tengah perbincangan mereka hingga terbahak-bahak, berita dari radio yang diletakkan di meja kasir membuat seluruh pengunjung The Turf Tavern terdiam.
Suara sirine memenuhi ruangan itu, memekakkan telinga. Samar-samar suara pembaca berita terdengar, bergemerisik. Sang kasir menepuk-nepuk radio bututnya untuk memastikan apakah radionya yang salah atau memang begitu keadaannya nun jauh di sana.
Suara sirine terdengar makin keras, disusul suara ledakan samar-samar.
Firasat Iris buruk, apalagi yang terjadi?
Benar adanya, 90 kilometer dari Oxford, tepatnya di pusat kota London, serangan bom diluncurkan oleh angkatan udara Jerman. Suasana restoran itu, dan di sekitarnya langsung ricuh. Pemilik restoran yang tadinya berdiri di belakang meja kasir dan mendekatkan kupingnya pada radio langsung menenangkan orang-orang di tempat tersebut.
Flint, Martha, dan Geoff saling memandang dengan mata ketakutan, banyak anggota keluarga mereka yang tinggal di London. Hanya keluarga Valentina dan Iris yang tinggal di Bristol dan Birmingham. Dengan buru-buru mereka bertiga mengemasi barang dan beranjak untuk pergi menghubungi keluarga masing-masing, namun dihadang oleh pemilik toko yang berseru dengan telepon mekanis di tangan kanannya.
“Kalian berlima! Ada panggilan dari Sir William untuk segera kembali ke Balliol dan melakukan pertemuan.” Ia memberikan teleponnya kepada Martha yang berdiri paling dekat dengannya.
“Sir! Bagaimana kau tau kita ada di sini?” Matanya terbelalak. “Eh, itu tak penting sekarang, Sir. Bolehkah beberapa dari kita meminta izin untuk menghubungi keluarga kita dahulu?”
“Martha, aku tau kondisimu sekarang, namun ini sangat darurat. Saya harap kerja samanya, Martha.” Lelaki tua itu menghembuskan nafas. “Bergegaslah kemari dan kalian bisa menghubungi keluarga nanti! Cepat, sebelum terlalu larut!”
Nada tegas lelaki yang menjabat sebagai ketua di Balliol College, salah satu universitas di Oxford itu membuat mereka berlima berlari menuju ke sana. Benar katanya, di luar sudah hampir malam, dingin, mereka terlalu lama bersenang-senang.
Sesampainya di aula Balliol, Sir William mengumandangkan pengumuman darurat kepada seluruh mahasiswa dan stafnya yang memadati aula untuk bergerak dalam pengeboman ini. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok: ada yang tetap tinggal di Oxford dan ada yang bertugas ke lokasi-lokasi pengeboman. Ia juga membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi sukarelawan.
Di bawah langit sore, ketika matahari hampir terbenam di ufuk barat, Oxford yang biasanya sibuk akan rutinitas akademisnya kini terasa lesu, muram, dan berisik. Orang-orang berebut untuk mengambil bagian mereka dalam tugas mulia tersebut. Jantung Iris yang berdegup kencang sedari mendengar kabar itu kini teringat akan keluarganya di Birmingham yang entah bagaimana keadaannya sekarang, ia berdoa agar serangan tak menyebar hingga ke sana. Juga Hugo, kakak laki-lakinya yang bertugas menjadi penyidik dan menjaga keamanan negeri dalam militer pada saat itu, entah bagaimana kondisinya.
Ia yakin Hugo bisa menjaga dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang tak bersalah? Bagaimana dengan keluarga teman-temannya? Atau, petugas militer yang membutuhkan pertolongan cepat? Iris membulatkan tekad untuk ikut bersama Valentina ke London.
Wajah Valentina seketika menjadi sumringah melihat Iris dengan yakin berjalan ke arah rombongan yang ikut dalam bagian medis.
“Nyonya Delamo, senior kita, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung!” Jane, mahasiswi yang baru masuk Balliol setahun lalu memegang tangan Iris dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang di sekitarnya ikut mengelilingi Iris, kebanyakan dari mereka adalah anak baru, hanya Iris, Valentina, dan sekitar dua belas orang lainnya yang berasal dari angkatan yang sama.
“Aku yakin kita semua bisa berjuang bersama sampai akhir.” Balas Iris. “Demi Inggris!”
Mereka mengepalkan tangan.
“Demi Inggris!”
***
Udara dingin menusuk tubuh Iris yang tak lagi terbungkus selimut, samar-samar ia mengintip dari balik jendela daun-daun oranye berjatuhan dan memenuhi jalanan asrama Balliol, ia tak ingin beranjak. Teringat mimpi buruk yang mempengaruhi alam bawah sadar dan kondisi tubuhnya hari ini, di sana, ia terlambat menyembuhkan Hugo, laki-laki itu gugur dalam menjalankan tugasnya.
Hari ini, sehari setelah penyerangan udara pertama Luftwaffe di London, Iris masih memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan obat-obatan dan mengatur suplai medis hingga tugasnya berangkat ke London terlaksana seminggu lagi. Kini ia sendirian, Valentina berangkat lebih dulu menuju lapangan.
Dia menggelengkan kepala, tak ingin terpengaruh oleh mimpi yang belum tentu benar adanya, masih ada tugas yang harus segera ia selesaikan. Iris berusaha untuk beranjak dengan seluruh badan kesakitan, tapi orang-orang di sana jauh lebih kesakitan.
***
Setidaknya itu yang ia lakukan selama seminggu kedepan: meracik obat, menyuplai barang-barang medis, dan memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berhasil mengungsi ke sekitar Oxford. Iris mengagumi betapa hebatnya mereka, bagaimana orang-orang itu bisa bersama-sama menyelamatkan diri dengan kondisi yang sudah tak karuan, namun dengan semangat mencari tempat perlindungan.
Iris memang masih seorang mahasiswa, tapi ia bangga telah menjadi tempat perlindungan pertama bagi mereka yang membutuhkan suaka. Hingga pada suatu sore, Iris mengajukan pernyataan untuk berangkat ke London lebih awal setelah ada pengumuman bahwa ia menjadi salah satu sukarelawan yang tanggal keberangkatannya diundur hampir sebulan.
“Baik jika itu memang yang kau inginkan, Nyonya Delamo.” Pimpinan tenaga medis menaikkan alisnya. “Segeralah bersiap dan berangkat malam ini, agar kau tiba esok fajar.”
“Terima kasih, Mrs!” Iris membungkukkan badan, berjalan perlahan meninggalkan ruangan itu, dan berlari kegirangan. Ia memberitahu rekan-rekannya tentang kabar gembira itu, dan mengemasi barang-barangnya.
***
London, Inggris, November 1940.
Sudah dua bulan Iris menjalankan tugasnya bersama Valentina dan rekan-rekan lain, dan sudah satu minggu Iris dipindah-tugaskan di shelter, namun sekali-dua kali konsisten untuk mengunjungi rumah sakit.
Ia tinggal bersama Valentina dan sudah terbiasa dengan gelapnya London yang terlihat seperti kota mati. Ia sudah terbiasa untuk berjalan mondar-mandir membantu warga di rumah sakit maupun shelter untuk menutup jendela serta tirai-tirai kamar dan ruangan mereka, mengecek apakah masih ada lampu yang menyala, dan memberikan pertolongan pertama dalam penerangan yang minim.
Sekali-kali Iris menghubungi orang tuanya, dan kakek-neneknya yang telah lama tinggal di Spanyol, tapi dia sama sekali belum bisa menghubungi Hugo, maka sekali-dua kali ia bertanya kepada beberapa rekan kakaknya yang sering berjaga di rumah sakit. Jawabannya masih sama: “Ia baik-baik saja”, atau “Sedang sibuk”, atau “Kami tidak tahu, maaf, Nyonya.”
Siang itu, Iris menggulung rambut pirangnya, merapatkan jaket, dan membagi teh hangat kepada anak-anak, sambil menjalani cek kesehatan rutin. Langit London mulai gelap, mendung, mungkin akan turun hujan petang ini. Kesempatan Iris untuk pergi sebentar, menilik keadaan rumah sakit tanpa terdeteksi oleh pasukan Luftwaffe yang entah dari arah mana datangnya.
Iris baru saja hendak pergi setelah berbincang dengan seorang nenek, salah satu pengungsi, ketika pimpinan medis di shelter itu memberi tahu berita penting.
“Ms. Delamo, telepon dari Mr. Hugo Delamo.”
Bola mata Iris melebar, ia berlari menuju ruangan komunikasi. “Hugo! Sudah lama sekali aku tidak–”
“Iris.” Suara dingin laki-laki itu membungkamnya. “Sudah tahu kabar terbaru Birmingham?”
Gadis itu menggeleng.
“Mereka akan menyerang Birmingham, sepertinya esok pagi. Aku sudah menghubungi ayah dan ibu untuk pergi ke Pelabuhan Dover hingga berlabuh di Swedia.”
Dada Iris terasa sesak mendengar kabar itu. “Bagaimana mereka bisa mencapai Dover dalam situasi seperti ini? Lalu, siapakah yang akan menjaga mereka di Swedia, Hugo?”
“Setidaknya, ada tempat yang tersedia di Swedia. Spanyol terlalu jauh untuk mereka yang sudah makin tua, Iris. Aku yang akan mengurus semuanya.” Hugo berdeham.
Pesan yang diterima dalam suasana tegang mengungkapkan apa yang paling ditakutkannya: “Iris, sebaiknya kamu juga segera pergi ke Spanyol. Kakekmu menunggu dan di sana relatif aman. Kamu perlu berlindung,”
Iris menolak, Hugo bisa saja mengirim orang tuanya tetapi tidak dengan dirinya. Masih banyak orang yang membutuhkannya. Namun nada tegas Hugo membungkam Iris. “Ada situasi buruk yang entah kapan datangnya, dan kamu harus pergi.”
Keduanya menutup telepon di saat hujan dan petir turun bersamaan.

***
Iris segera memberitahu kabar itu kepada Valentina esok paginya karena cuaca semalam tidak memungkinkannya untuk meninggalkan shelter. Valentina menggelengkan kepalanya.
“Aku tahu Hugo mengetahui segalanya dibanding siapapun di saat seperti ini, tapi aku tidak ingin kamu pergi.”
Temannya itu peka sekali terhadap penderitaan pasien-pasien di rumah sakit ini. Iris selalu menyaksikan Valentina bekerja tanpa henti, memberikan semangat bagi pasien yang terbaring lemah. Valentina ingin Iris menemaninya untuk membantu warga London, dan saling menguatkan. Walau Iris memberi opsi agar ia ikut pergi, Valentina menolaknya. “Aku juga punya keluarga di Bristol, Iris. Aku memang tidak tahu kabar mereka, tapi setidaknya kami masih tinggal di negara yang sama.”
“Aku tahu perasaanmu Valentina, dan sampai saat ini aku juga masih peduli dengan orang-orang ini, bahkan aku berpikir untuk mendedikasikan sisa hidupku di sini.” Iris menelan ludah. “Tapi aku tidak bisa menyangkal pernyataan Hugo tentang situasi yang akan datang, aku sangat percaya perkataanya. Dia kepercayaan militer, Valentina. Dia tahu apa yang kita semua tidak tahu.”
Iris melanjutkan bahwa mereka bisa bertanya kepada Hugo terkait kondisi keluarga Valentina. Esok harinya, kabar datang secepat kilat dari laki-laki tersebut.
***
Orang tua Valentina dan adik kecilnya telah bergabung dalam tim evakuasi warga sipil dan berlabuh di Laut Utara menuju Norwegia. Sejak saat itu, Valentina secara bulat menyatakan bahwa ia akan ikut pergi bersama Iris. Dengan semangat yang menggelegar, mereka menyiapkan perjalanan. Selain itu, Iris harus meyakinkan Hugo agar Valentina ikut bersama mereka, dengan pesan yang dituliskan secara hati-hati.
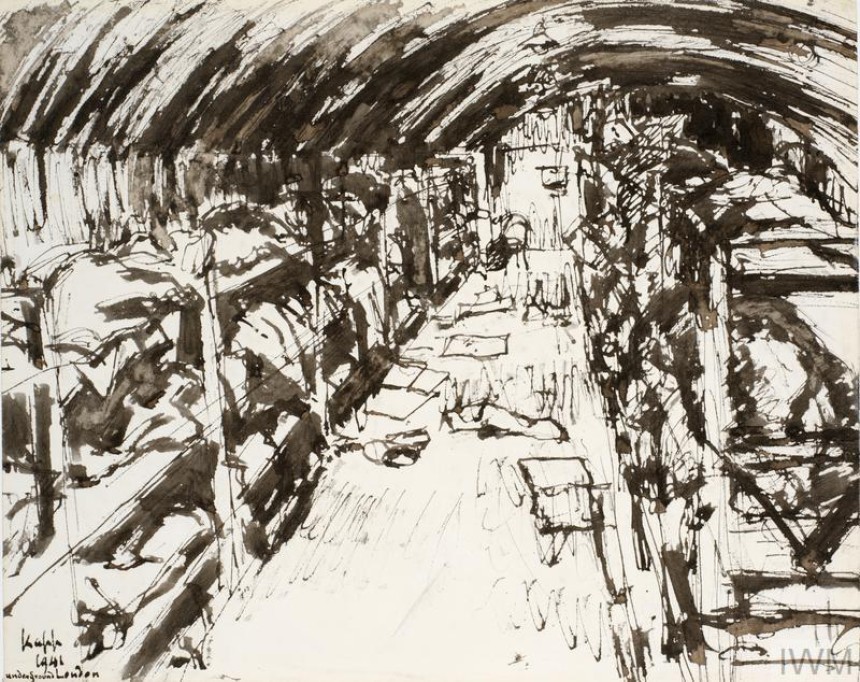
***
Desember 1940
Hugo mengirim Iris dan Valentina kepada rekannya sendiri, Sir Stewart Menzies, kepala MI6. Sir Menzies menjamu mereka dengan teh hangat dan roti sambil memberikan sejumlah informasi:
“Ada satu kapal militer di Pelabuhan Portsmouth yang akan ikut berjaga di sekitar Prancis, aku sudah meminta mereka untuk berlabuh di Spanyol sebentar, dan kalian harus cepat.” Sir Menzies berdeham. “Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Pesawat Jerman bisa saja menyerang kapal itu.”
Ia melanjutkan, “Ada beberapa kapal lain yang ikut berlabuh bersama, jika ada serangan, mereka akan mengirim sinyal. Kalian akan tetap terlindungi, dan ingat, aku menjaga kalian dari dalam kapal.”
***
Ketika Iris dan Valentina telah sampai di Pelabuhan Portsmouth, langit mendung membuat suasana menjadi menegangkan. Badai akan tiba, lebih baik mereka mempercepat langkah ke dalam kapal yang sudah terlihat di depan mata. Namun, saat mereka bersiap untuk naik, sirine peringatan dari pelabuhan tiba-tiba berbunyi.
Mirip dengan suara sirine di radio Oxford, suara melengking itu memicu kepanikan di pelabuhan. Pesawat-pesawat Jerman muncul di angkasa, terbang rendah dengan tujuan menyerang kapal-kapal di pelabuhan. Tim keamanan pelabuhan terlihat panik berusaha mengarahkan warga sipil ke tempat berlindung. Pun anggota militer yang berkumpul dan berusaha untuk menahan serangan. Iris, Valentina, dan Sir Menzie terpisah di antara kerumunan yang kacau balau mencari tempat perlindungan.
“Valentina!” Iris menjerit mencari Valentina di tengah kerumunan, di sisi lain Valentina mengetahui posisi Iris dan berusaha meraih tangannya.
Hati Iris berdegup kencang ketika pesawat menjatuhkan bom lain. Orang-orang di sekitarnya mulai berjatuhan. Namun, pada titik kritis, sebuah ledakan menghancurkan bagian dekat dermaga, menjatuhkan puing-puing kayu dan batu ke arah mereka. Valentina gagal meraih tangan Iris dan mereka terpisah di antara lautan puing dan manusia yang berjatuhan.
Setelah situasi mulai mereda, Iris membuka dekapannya pada radio portabel yang diberikan oleh Sir Menzie, mencoba menghubunginya dan Valentina. Tidak ada jawaban.
Sir Menzie dan awaknya di kapal mengalami situasi menegangkan saat persiapan untuk berangkat ke Prancis dilaksanakan. Kapal diharuskan untuk menunggu hingga situasi aman untuk berlayar. Di sisi lain, terdapat tekanan untuk segera berangkat karena ada informasi mengenai serangan udara yang lebih besar dan mereka sedang dalam perjalanan kemari.
“Bukankah lebih baik jika kita membantu operasional evakuasi terlebih dahulu dengan menjemput warga sipil yang tersisa di pelabuhan dan militer lainnya untuk ikut bergabung?” Salah satu anggota militer menyampaikan usulannya.
“Tapi itu bertentangan dengan misi pelayaran kita!” Sahut lainnya.
“Abaikan misi pelayaran itu! Dua anak yang seharusnya di sini belum ditemukan, dan kita harus menunggunya!”
Akhirnya Sir Menzie memutuskan untuk memberi waktu satu jam sebelum kapal benar-benar berlayar.
Sementara, di markas MI5, Hugo menerima kabar dari intel bahwa pasukan menyapu Pelabuhan Portsmouth hingga Southampton. Ia segera meraih telepon dan menghubungi Sir Menzies.
“Sir, saya perlu tahu apakah Iris dan Valentina sudah sampai di dalam kapal. Mereka bisa dalam bahaya!”
Mendengar bahwa mereka belum sepenuhnya tiba dan situasi semakin buruk, Hugo memutuskan untuk turun tangan. Ia meminta izin kepada komandannya untuk terjun ke lapangan, sesaat setelah komandan menyetujui Hugo pergi sebagai pasukan militer.
Laki-laki itu bergegas menuju battalion di dekat pelabuhan, mengambil senjata dan pelindung diri yang diperlukan. Ia berjalan mendekati pelabuhan, melewati jalan-jalan yang penuh kekacauan dan reruntuhan. Dalam perjalanannya, dia menjumpai sekelompok tentara dan meminta mereka untuk membantunya mencari Iris dan Valentina sebelum situasi menjadi lebih parah.
Sesampainya di pelabuhan, mereka melihat pesawat Luftwaffe berputar-putar di dekat kapal yang akan berlabuh. Tak jauh dari posisinya, salah satu tentara melihat bayang-bayang Valentina yang mendekap seorang anak yang tergeletak di tanah. Hugo segera menjemputnya dan mencari tempat perlindungan.
Saat Morales, seorang tentara memberi sinyal bahwa pesawat Jerman akan menyerang kembali, Valentina beranjak dan mengajak Hugo untuk mencari Iris. “Cepat! Kita harus bertindak!”
Dalam proses pencariannya, mata Hugo menangkap Iris dengan kakinya yang terluka parah, ia berteriak memanggil namanya. “Iris! Langsung ke kapal!”
Hugo pun menyuruh Morales berlari untuk mengantar Iris karena tak bisa menyelamatkan dua orang sekaligus dalam waktu yang singkat, jarak mereka dengan kapal hanya tersisa beberapa ratus meter lagi.
Di atas mereka, pesawat dari arah Southampton menjatuhkan deretan bom berikutnya yang membuat keempat orang itu mempercepat langkah. Gerbang kapal sudah terlihat beberapa meter lagi. Iris sekuat tenaga menahan rasa sakit dari darah yang semakin mengucur dari tungkai kanannya, ketika ia melihat Valentina dan Hugo sudah hampir tiba, ia menghempas rasa sakit itu.
Puing bangunan dari dekat dermaga berjatuhan di langkah-langkah terakhir menuju kapal, Morales dengan sigap menarik Valentina menjauh, sementara Hugo terdorong ke belakang, kakinya terjepit di antara puing bangunan. Iris berusaha untuk menariknya namun ditepis oleh Morales yang meminta mereka segera naik sebelum terlambat.
“Tidak!” Valentina bersikeras untuk menunggu Morales dan Hugo.
“Tidak ada waktu, Valentina! Kita harus menuruti Morales!” Iris menarik tangan Valentina dan menaiki tangga menuju kapal.
Di kapal, Sir Menzies melihat kekacauan dari jauh. Merasa bertanggung jawab, dia segera menginstruksikan awak kapal untuk membantu evakuasi. Ia berteriak ke arah dermaga.
“Satu menit lagi sebelum kami berlayar! Siapa pun yang ada di sana, kalian harus segera!”
Di detik-detik krusial itu, Iris berseru agar Hugo dan Morales segera menuju kapal. Hugo sudah bisa berlari dan mereka berdua berhenti di dekat dermaga. Iris berseru lagi, namun baik Hugo maupun Morales tidak beranjak dan kapten kapal menginstruksikan untuk berlabuh.
“Kita harus bersama, Hugo! Morales!” Teriak Iris.
“Berhati-hatilah, aku akan menemukanmu di Spanyol! Ini memang tugasku untuk melindungi kalian.”
Hugo menyaksikan adiknya pergi, berusaha keras melawan kesedihan yang mengguncang dirinya. Dengan situasi yang semakin genting, Hugo dan Morales berjuang untuk membebaskan diri, sementara Iris dan Valentina berlayar menuju ketidakpastian di tempat yang lebih aman–nihilnya jaminan bahwa mereka akan bertemu lagi.
Cerita Narasi: Sihir Mengubah Segalanya
Sebuah cerita fantasi karya Aviva Octavia



